Krisis Industri Keuangan Negara Adidaya
TEMPO Interaktif, Jum'at, 10 Oktober 2008 | 14:41 WIB
Cyrillus Harinowo
PADA Mei 2004, saya menyelenggarakan Seminar ”Dollar Versus Euro” di Hotel Shangri-La. Euro belum sekuat saat ini, tapi saya percaya mata uang Eropa itu akan menjadi jangkar dalam peta keuangan dunia. Sayangnya, kesimpulan seminar tersebut agak jauh dari dugaan saya, yaitu dolar Amerika masih akan tetap kuat, sementara euro belum memiliki kekuatan yang dapat dibandingkan dengan dolar. Ketidakpuasan saya itu akhirnya saya tuangkan dalam tulisan ”Membaca Tanda-tanda Zaman” di majalah Tempo beberapa minggu kemudian.
Tulisan tersebut merupakan hasil pengamatan saya atas perkembangan perekonomian makro selama pemerintahan Bush. Defisit anggaran mulai menggelembung, juga defisit neraca pembayaran. Utang pemerintah Amerika naik tajam. Saya memprediksi perekonomian Amerika akan mengalami crash dan euro menguat. Hati saya terpecah. Di satu sisi, saya ingin melihat prediksi saya terbukti. Di sisi lain, saya tahu persis bahwa crash perekonomian sebuah negara adidaya akan membawa konsekuensi yang luas pada perekonomian dunia.
Pada 2005 ternyata saya tak melihat prediksi itu menjadi kenyataan. Perekonomian Amerika ”baik-baik saja”. Demikian juga tahun berikutnya. Namun euro menguat secara bertahap. Pada 2007, prediksi mulai menjadi kenyataan, meskipun penyebabnya berbeda. Dari pemetaan itu, krisis yang terjadi dalam industri keuangan Amerika akhirnya menemui ujungnya: beban utang pemerintah Amerika naik tajam.
Berawal dari ketamakan
Krisis berawal dari problem yang timbul pada kredit perumahan. Kredit perumahan yang awalnya berjalan baik karena ditujukan kepada nasabah prima akhirnya meluas kepada nasabah-nasabah yang tidak layak. Nasabah yang pernah dilanda kredit macet memperoleh kembali kredit baru. Selain itu, banyak kredit yang diberikan dengan uang muka yang sangat rendah, yaitu lima persen, atau bahkan tanpa uang muka sama sekali. Banyak pula kredit yang hanya mempersyaratkan pembayaran bunga (interest only) dan tidak mewajibkan nasabah membayar cicilan pokok sama sekali.
Mengapa perbankan Amerika sampai amat teledor? Jawabannya adalah karena harga-harga properti naik tajam bertahun-tahun tanpa henti. Dengan harga rumah yang naik terus, nilai jaminan (harga rumah) juga meningkat, sedangkan jumlah pinjaman pokoknya tetap.
Karena itu, dalam perhitungan bank, walaupun tanpa uang muka, jika harga naik 20 persen per tahun, nilai jaminan akan menjadi 120 persen dari harga awal. Sehingga nilai pinjaman dibandingkan dengan jaminan turun menjadi 83 persen. Seolah-olah pada akhir tahun pertama si nasabah sudah membayar uang muka 17 persen. Inilah yang disebut loan to value ratio. Situasi itulah yang membuat bank berani memberikan kredit pemilikan rumah tanpa uang muka. Bermacam-macam kredit itulah yang disebut sebagai subprime.
Apakah kenaikan harga rumah 20 persen itu betul-betul terjadi? Seorang teman Indonesia yang tinggal di Washington, DC, membeli rumah pada 1998 dengan harga US$ 210 ribu dan lima tahun kemudian menjualnya seharga US$ 410 ribu. Dengan situasi itu, seolah-olah ia tinggal lima tahun tanpa membayar, bahkan dibayar. Di banyak kota, kenaikan harganya sering lebih ”gila”. Itulah sebabnya banyak orang memberanikan diri mengajukan pinjaman pembelian rumah kedua untuk disewakan—uang sewanya dipakai untuk membayar cicilan.
Fenomena seperti ini bisa terjadi karena harga rumah naik terus. Hanya, kenaikan harga secara sistemik seperti itu cuma terjadi jika orang yang membeli rumah makin banyak. Juga jika bank terus memasok perekonomian dengan kredit pemilikan rumah yang makin besar. Tapi, karena nasabah bank tidak semuanya nasabah prima, bahkan banyak yang ”kambuhan” kredit macet, penyakit lama itu mulai muncul. Pembayaran cicilan pun mulai seret.
Karena keadaan itu, bank mulai hati-hati menyalurkan kredit. Dampaknya, kehati-hatian bank tersebut menyebabkan harga rumah berhenti naik, bahkan mulai turun. Penurunan harga itu menyebabkan nasabah kredit pemilikan rumah mulai berpikir apakah akan meneruskan cicilan atau ngacir saja. Akhirnya, kredit macet pun membesar. Jadilah problem kemacetan kredit subprime menggelinding seperti bola salju.
Maraknya derivatif subprime
Di Amerika Serikat, industri keuangan sudah demikian ”maju”-nya. Kredit-kredit perumahan itu akhirnya oleh bank yang bersangkutan dikumpulkan dan kemudian disekuritisasi. Ini adalah suatu proses mentransformasikan kredit pemilikan rumah menjadi surat berharga (sekuritas). Istilah yang sering dipergunakan untuk surat berharga yang dijamin oleh kredit pemilikan rumah tersebut adalah mortgage back securities (MBS) dengan varian yang bernama collateralized debt obligation (CDO).
Nasabah tetap membayar cicilan kepada bank asalnya, tapi bank itu kemudian meneruskan pembayarannya kepada pihak yang membeli surat berharga tersebut. Jika pembayaran cicilan lancar, pembayaran dari bank kepada pemegang surat utang juga lancar. Namun, karena pembayaran dari nasabah sebagian mulai batuk-batuk, pembayaran kepada pemilik MBS dan CDO tersebut juga tersendat. Siapa pemegang dua jenis surat utang itu?
Proses sekuritisasi kedua varian surat utang tersebut banyak dibantu oleh lembaga keuangan yang awalnya didirikan pemerintah Amerika untuk tujuan itu, yaitu Fannie Mae dan Freddie Mac. Karena tugas tersebut, kedua lembaga itu juga memberikan jaminan. Juga karena perannya, mereka akhirnya memiliki ”stock” MBS dan CDO yang belum laku atau mereka memang ingin memilikinya.
Dengan peran seperti itu, begitu terjadi kisruh pembayaran cicilan MBS dan CDO, pasar memperkirakan kedua lembaga yang sahamnya sudah dicatatkan di New York Stock Exchange itu pasti rugi besar. Investor pun rame-rame melepas saham kedua perusahaan itu, yang berujung pada anjloknya harga saham. Dalam keadaan yang sudah amat kepepet, pemerintah Amerika menolong kedua lembaga itu.
Lembaga lain yang memiliki MBS dan CDO amat banyak, antara lain bank besar seperti Citigroup atau UBS. Karena nilai kedua jenis surat utang tersebut jatuh, bank-bank itu harus mulai melakukan ”penghapusan” (write down), yang akhirnya membuat mereka rugi dan modalnya tergerus. Investor pun melepas saham bank-bank itu, sehingga harga saham mereka pun ikut ambles.
CDS, derivatif yang sangat beracun
Beberapa bank investasi juga memiliki MBS dan CDO itu, sehingga mereka pun merugi. Tapi ternyata yang menjadi masalah lebih besar adalah ditemukannya instrumen keuangan baru (derivatif) yang bernama credit default swap (CDS).
Instrumen ini pada awalnya punya tujuan baik, yaitu memberikan ”asuransi” bagi pemiliknya jika kredit (bisa obligasi atau surat berharga lain, termasuk MBS dan CDO) yang mereka miliki terkena masalah. Yang tidak baik adalah pelaksanaannya kemudian. Lagi-lagi masalah ini timbul karena dimulai dari ketamakan.
Sebuah perusahaan yang memiliki obligasi ingin melindungi dirinya dari kemungkinan obligor gagal bayar dengan membeli asuransi yang disebut CDS itu. Dengan begitu, mereka memiliki kepastian mengenai nilai obligasi itu meskipun harus membayar premi. Perusahaan yang mengeluarkan asuransi itu di pihak lain juga harus menyisihkan dananya sebagai ”kolateral”. Jika obligasi itu akhirnya gagal bayar, perusahaan tersebut memiliki uang untuk membayar kerugian kepada pihak yang membeli asuransi tadi.
Dalam perjalanannya, perusahaan yang mengeluarkan CDS ternyata banyak yang tidak menyisihkan kolateral. Yang lebih parah, CDS yang sama diperjualbelikan. Dengan cara ini, mereka menerima premi yang besar, sehingga akhirnya dapat menghasilkan ”laba” yang kian besar. Dengan laba yang naik tajam ini, bonus juga sangat besar. Kalau obligasinya tetap lancar, transaksi seperti ini tentu amat menggiurkan. Tapi, karena MBS dan CDO mulai bermasalah, pihak asuransi pun mulai banyak diklaim. Di sinilah kerugian yang sangat besar terjadi.
Jumlah kerugian kolosal itu akhirnya memaksa pemerintah Amerika mengambil langkah darurat. Sebagian lembaga keuangan dibantu, seperti Bear Stearns, Merrill Lynch, dan AIG. Goldman Sachs dan Morgan Stanley juga dibantu dengan diizinkan ”bermutasi” menjadi bank komersial. Yang dibiarkan jatuh adalah Lehman Brothers. Bantuan itu akhirnya dibuat menjadi terstruktur dengan jumlah yang diusulkan US$ 700 miliar.
Beban utang yang menimbulkan keraguan
Upaya penyelamatan US$ 700 miliar mestinya bisa menenangkan pasar. Tapi ternyata jumlah itu menimbulkan keraguan baru, yaitu dari sisi kesehatan keuangan pemerintah Amerika. Inilah inti yang saya bicarakan di awal artikel ini dalam ”Membaca Tanda-tanda Zaman”.
Jumlah utang pemerintah kini mencapai US$ 9,7 triliun dan tiap hari bertambah US$ 1,8 miliar. Dengan upaya penyelamatan itu, batas atas utang pemerintah ditetapkan US$ 11,3 triliun. Jika ini tercapai, rasio utang Amerika terhadap produk domestik bruto akan mencapai 80 persen dan akan naik terus. Pada masa pemerintahan yang akan datang, siapa pun presidennya, bukan tidak mungkin rasionya meningkat menjadi 100 persen.
Karena itu, pemerintah dituntut lebih keras bekerja, mengencangkan ikat pinggang, sehingga meledaknya beban utang itu tidak lepas kendali. Topik itu sampai kini belum menjadi agenda pemerintah Bush. Ini berbeda dibandingkan dengan pemerintah Clinton, yang sukses menekan defisit dan bahkan mencetak surplus anggaran dalam tiga tahun terakhir pemerintahannya. Amerika memiliki tanggung jawab yang amat besar untuk mencegah krisis itu menghancurkan perekonomian dunia.
Cyrillus Harinowo, Rektor ABFII Perbanas
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Rafael V. Mariano, chairperson of the Peasant Movement of the Philippines, 2000
Food has long been a political tool in US foreign policy. Twenty-five years ago USDA Secretary Earl Butz told the 1974 World Food Conference in Rome that food was a weapon, calling it 'one of the principal tools in our negotiating kit.' As far back as 1957 US Vice-President Hubert Humphrey told a US audience, "If you are looking for a way to get people to lean on you and to be dependent on you in terms of their cooperation with you, it seems to me that food dependence would be terrific."
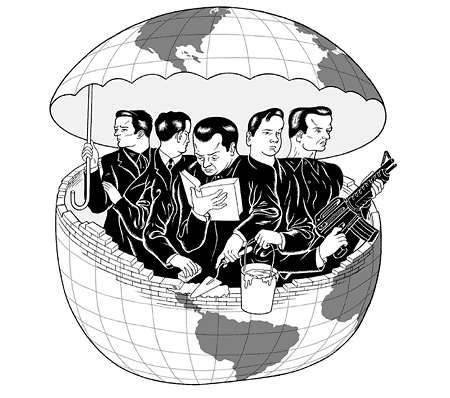


No comments:
Post a Comment