
Pada tanggal 15 Agustus 1971 Presiden Nixon mengumumkan sebuah kebijakan yang mengubah dunia dan perekonomiannya untuk selama-lamanya. Pengumuman ini mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak lagi mau menanggung mata uang dunia untuk membeli emas dengan dollar. Sejak hari yang bersejarah itu, apa yang disebut "Sistem Bretton Woods" tamat riwayatnya. Mata uang di dunia tidak lagi dikaitkan dengan dollar AS, dan dibiarkan mengambang (float) di pasar bebas, mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Padahal Sistem Bretton Woods (yang disebut fixed exchange rate) ini telah membuat sistem keuangan dunia sejak akhir Perang Dunia II stabil selama lebih dari 25 tahun. Beberapa negara masih mencoba mencari alternatif Sistem Bretton Woods (misalnya Smithsonian Agreement), tetapi sia-sia. Pada 12 Februari 1973 Jepang memutuskan untuk mengambangkan mata uang yen mengambang terhadap dollar, pada 16 Maret 1973 European Community mengikuti jejak. Negara-negara lain menyusul mengambangkan mata uangnya terhadap dollar.
Di dunia bukannya belum pernah ada "money market" tetapi apa yang diakibatkan oleh pengumuman Nixon itu adalah bahwa pasar uang itu menjadi kegiatan yang berdiri sendiri, terlepas dari kegiatan perdagangan komoditas. "Foreign exchange market" dianggap sebagai sebuah instrumen dari banyak instrumen lain yang dipakai oleh investor, tetapi dalam waktu singkat sejak hari yang bersejarah itu pasar valuta asing itu menjadi makin lama makin besar. Misalnya, kegiatan jual-beli valuta asing setiap harinya pada tahun 1977 hanya sejumlah US$ 18.3 milyar, dalam waktu tiga tahun telah naik menjadi US$ 82,5 milyar, dan 20 tahun sesudahnya sudah menjadi US$ 1,49 trilyun. (Singh, 13).
Sebagai perbandingan, pada tahun 1970, 90 persen dari transaksi valas dipergunakan untuk perdagangan dan investasi. Kini perdagangan valuta asing hampir tidak ada hubungannya dengan perdagangan internasional. Pertumbuhan perdagangan valas itu sendiri menjadi sangat cepat. Misalnya, pada tahun 1998 perdagangan valas sebesar US$ 1,49 trilyun, sementara perdagangan barang dan jasa sebesar US$6,5 trilyun, atau hanya empat hari kerja bagi perdagangan valas.
Pada abad ke-21 ini perdagangan valas berlangsung selama 24 jam, tidak pernah tidur atau istirahat. Ketika Jakarta tutup pada jam 17.00, Mumbay masih aktif, Frankfurt dan London mulai buka, dan 6 jam kemudian New York menyusul. Perdagangan terus berlangsung tanpa henti. Ini akibat dari kemajuan alat komunikasi yang sangat hebat selama 20 tahun terakhir, seperti telpon, facsimile, internet, telpon genggam, dsb. Semua alat komunikasi itu, terutama komputer, terus memutar uang ke seluruh dunia!
Mengapa bisa menjadi seperti ini? Nilai mata uang itu naik-turun, tidak ada yang mampu meramalkan. Sebelum runtuhnya Sistem Bretton Woods tidak mungkin terjadi seperti ini. Sekarang nilai mata uang ditentukan semata-mata oleh mekanisme pasar, dan dengan demikian mengandung unsur volatile, orang setiap kali main tebak apakah nilai mata uang tertentu naik atau turun. Karena tidak menentu inilah, kedua, orang malah semakin bergairah untuk masuk dalam transaksi valas. Pada dasarnya jual-beli valas ini nyaris tidak ada bedanya dari perjudian. Keuntungan yang diraup dengan satu sentuhan tombol komputer, bisa sedemikian besar. Tapi kerugian dahsyat juga bisa menimpa akibat sebuah klik petikus. Tidak heran kalau Susan Strange, seorang pengamat terkenal di bidang keuangan internasional, mengatakan bahwa dunia saat ini sedang dicengkeram oleh "casino capitalism."
Akibat dari perilaku ini sangat mengerikan bagi ekonomi dunia, ekonomi nasional, dan ini pada gilirannya mengerikan bagi politik. Pertama, karena semangat berjudi itu, para pelaku terdorong untuk mengalihkan dananya dari investasi yang produktif yang sifatnya jangka-panjang (long term), dan memilih keuntungan spekulatif yang sifatnya jangka pendek (short term). Maka ekonomi riil di bidang manufaktur ataupun jasa, semuanya dalam keadaan terdesak. Kedua, akibat dari gairah yang berlebih ini, bank-bank dan institusi keuangan cenderung untuk mematok suku bunga yang tinggi. Hal ini juga berdampak pada ekonomi riil karena pengusaha menghadapi kendala untuk memperoleh akses kredit. Ketiga, akibat dari kegiatan spekulatif, terjadilah ketidakpastian dan volatilitas suku bunga dan nilai tukar. Volatilitas ini sangat merugikan sektor-sektor ekonomi riil, terutama perdagangan. Terakhir, perdagangan valas ini juga memaksa negara-negara untuk mengambil kebijakan yang merugikan bagi pencari kerja dan sekaligus juga menimbulkan ketimpangan (inequality).
Kasus yang paling jelas adalah Krisis Finansial 1997 yang menimpa Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara (Thailand) dan Asia Timur (Korea Selatan). Para spekulan mula-mula menyerang Thailand, dan ini menimbulkan kepanikan yang berbuntut pada serangan ke negara lain yang juga menganut rejim devisa bebas. Demikian terjadi rantai "serangan"oleh spekulan yang bergerak dari satu negara ke negara lain, tanpa ada satu otoritas pun yang bisa mengendalikannya. Indonesia, Thailand dan Korea Selatan bertekuk lutut pada kekuatan spekulan (menurut Kwik Kian Gie, cuma dibutuhkan US$ 100 ribu dollar untuk membuat pasar keuangan sebuah negara ambruk!). Berbeda dari Thailand dan Korea Selatan, Indonesia mengalami kehancuran ekonomi dan juga politik.
Banyak analis ketika itu yang mengatakan bahwa Krisis Keuangan itu akibat crony capitalism, atau korupsi. Tetapi bagaimana dengan India yang juga dilanda korpusi, tidak mengalami krisis keuangan? Juga bagaimana Inggris pada 1992 yang bebas dari korupsi juga mengalami krisis keuangan? Banyak ahli akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa penyebab Krisis Keuangan itu adalah casino capitalism. Dan ini pada akhirnya bermuara pada "rejim devisa bebas" yang dianut oleh negara-negara yang tertimpa krisis itu.
Maka diskusi tentang perdagangan valuta asing kini berputar-putar pada satu titik: kapan sebuah negara menerapkan rejim devisa bebas? Para pendukung radikal globalisasi (yang mengangut paham ekonomi neoliberal) berpendapat bahwa semua negara di seluruh dunia menganut rejim devisa bebas. Tapi banyak ahli mengatakan bahwa "financial liberalization" tidak selalu membawa manfaat bagi negara yang sedang membangun. Mereka mengajukan contoh-contoh dari masa lalu, maupun contoh masa sekarang. Cina adalah contoh yang paling gamblang. Karena Cina tidak menganut rejim devisa bebas, Cina pun terhindarkan dari gempuran spekulan tahun 1997 itu.
Sangat menarik bahwa rejim devisa bebas atau financial liberalization ini menjadi pokok perdebatan yang menjurus kepada ideologi. Ideologi neoliberalisme (lihat posting tentang pasar bebas) kini bergabung dengan ideologi globalisme (lihat Manfred Steger), menghasilkan penganut-penganut setia dan loyal. Cara analisis mereka tentang pasar bebas (termasuk pasar bebas keuangan) didasarkan keyakinan semata-mata, sehingga menghasilkan apa yang disebut "market fundamentalism." Sebagai fundamentalis, orang-orang itu sulit menerima masukan bahwa financial liberalization itu mendatangkan petaka.
Tidak mungkin bicara tentang perdangangan valas tanpa membicarakan institusi global di bidang keuangan, yaitu IMF (International Monetary Fund). Ketika IMF didirikan sebagai bagian dari "Bretton Woods Institution," lembaga ini diberi mandat untuk menolong negara-negara yang mengalami kesulitan balance of payment. Negara-negara yang mengalami krisis (termasuk Indonesia) dan mengundang IMF, diperintahkan untuk menjalankan rejim devisa bebas. Bukankah krisis keuangan itu akibat dari rejim devisa bebas, tapi mengapa obat untuk mengatasi krisis malah berupa tuntutan untuk melaksanakan rejim devisa bebas? IMF terkenal dengan resepnya yang disebut SAP (structural adjustment programme), yang salah satunya adalah perdagangan bebas.
Kritik terhadap IMF (juga World Bank dan World Trade Organization) dapat diperpanjang, tetapi yang utama di sini adalah di jaman sekarang sedang terjadi keanehan besar. Dunia kini tenggelam dalam sebuah mesin kasino besar, yang dimainkan oleh segelintir orang, tapi yang merugikan puluhan juta manusia. Banyak orang telah bicara tentang perlunya "Global Governance" untuk mencegah terulangnya malapetaka. Di antaranya adalah George Soros, seorang spekulan kondang. Tapi, hingga hari ini, pembicaraan itu tidak beranjak ke mana-mana.
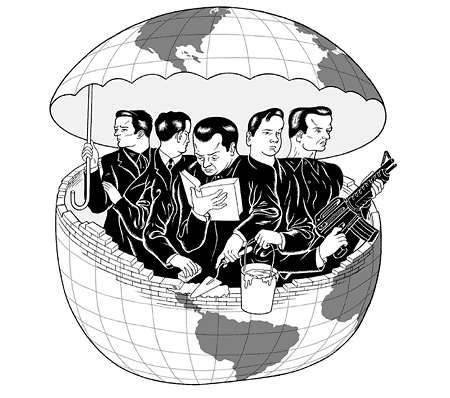


No comments:
Post a Comment