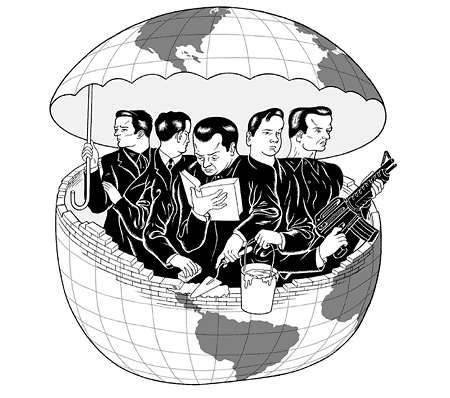Jumat, 25 Januari 2008 | 11:31 WIB
PARIS,KAMIS - Meski Societe Generale (SocGen), belum mengungkapkan siapa pembobol 4,9 miliar euro (sekitar Rp 67 triliun) bank terbesar di Perancis itu, namun media sudah mengungkapkannya. Dia adalah Jerome Kerviel, pria Perancis berusia 31 tahun dan sudah bekerja di Societe Generale sejak tahun 2000.
Pihak Societe mengungkapkan adanya seorang pialang di Paris melakukan transaksi fiktif yang massive sehingga merugikan bank terbesar di Perancis itu sampai Rp 67 triliun. Kasus itu merupakan pembobolan terbesar dalam sejarah perbankan, atau empat kali lebih besar dibandingkan kasus Nick Leeson, pembobol bank Inggris, Barings. Akibat ulahnya tahun 1995 lalu yang merugikan Barings 860 juta pound, Leeson dipenjara 6,5 tahun. Seperti dikutip BBC, Leeson mengaku tidak terkejut dengan ulah Kerviel itu."Transaksi fiktif mungkin terjadi hampir tiap hari dalam pasar finansial," katanya.
Yang mengejutkan, lanjut Leeson, adalah jumlah kerugian yang ditimbulkan Kerviel yang mencapai Rp 67 triliun. "Yang mengejutkanku hanya nilainya. Saya tidak pernah menyangka kadar kerugiannya sebegitu besar," katanya.
Menurut media, Kierval bekerja di Bank Delta One di Paris. Meski pihak SocGen belum mengkonfirmasikan kebenarannya, bank tersebut menyebutkan pialang tersebut adalah orang Perancis, berumur 30an, bekerja sejak tahun 2000 serta mendapat bayaran dan bonus setidaknya 100.000 euro. "Dia bertanggung jawab akan masa depan pasar," sebutnya seorang executive bank.
Dikatakan, Chief Executive of the corporate and investment banking division, Pierre Mustier, si pembobol melakukannya seorang diri. Menurut pihak bank, pialang tersebut sudah mengakui perbuatannya dan telah dipecat. Demikian juga dengan managernya.
Akibat pembobolan itu, Societe harus mencari dana 5,5 miliar euro (sekitar Rp 75 triliun) untuk menutup kerugiannya. Namun disebutkan Societe tetap mendapat laba 600 juta-800 juta euro pada tahun 2007.
Sebagai salah satu bank terbesar di Perancis, Societe Generale didirikan tahun 1864, mempunyai 120 ribu karyawan di 77 negara, dengan 22,5 juta nasabah diseluruh dunia. Sampai Juni 2007, Societe mempunyai aset 467 miliar euro.
Sementara itu seperti dirilis Dow Jones, Menteri Keuangan Perancis meminta Presiden Bank Sentral Perancis meningkatkan pengawasan terhadap bank-bank, untuk menghindari terjadinya pembobolan bank seperti yang terjadi SocGen tersebut
Kompas,
PARIS,MINGGU - Jerome Kerviel, yang telah menghanguskan uang Rp 67 triliun di tempat kerjanya, Societe Generale, salah satu bank terbesar di Perancis, tanpa disadari telah menjadi pahlawan, menurut The Independent, Minggu (27/1), si manusia 5 miliar euro ini, secara tidak sengaja telah menyelamatkan dunia dari resesi. Namun meski demikian karena ulahnya yang merugikan SocGen, pria berusia 31 tahun ini ditahan oleh polisi di Paris dengan dikenai 3 tuduhan.
Kerviel menyatakan dirinya siap menjelaskan - bila dia dapat- bagaimana transaksi larut malamnya di bursa berjangka bisa menghilangkan 4,9 miliar euro (sekitar Rp 67 triliun) milik SocGen.
Chairman SocGen, Daniel Bouton, mengatakan, ulah Kerviel telah menjerumuskan pasar saham Eropa pada awal pekan lalu. Saham SocGen Senin (21/1) terutama di Jerman langsung jatuh, sehingga mendorong kepanikan di seluruh bursa. Yang pada akhirnya "memaksa" Federal Reserve (the Fed/bank sentral AS) untuk mengambil tindakan, the Fed Selasa (22/1)secara tidak terduga menurunkan sukubunga hingga 75 basis poin - terbesar dalam sejarah - hingga menjadi 3,5 persen untuk mencegah merembetnya kerontokan bursa Eropa, ke Wall Street yang sudah terpuruk dihantam badai kredit macet berbasis perumahan (subprime mortgage) sehingga bisa memicu resesi ke seluruh dunia.
Aksi Kerviel yang disertai reaksi the Fed, membuat beberapa ekonom AS mengelu-elukan Kierval sebagai sang penolong. "Merci, Jerome. Resesi hampir berlalu, terima kasih kepada Jerome Kerviel di Paris dan reaksi panik (the Fed) di Washington," kata seorang analis ekonomi berpengaruh Ed Yardeni, yang mantan kepala ekonom Deutsche Bank Securities.
Ya, dengan reaksi the Fed yang menurunkan sukubunga demikian tajam, pasar finansial di seluruh dunia merespon baik. Bursa saham yang tadinya bergelimpangan ke level terendah (termasuk Bursa Efek Indonesia), mulai menunjukkan gairahnya kembali. Rata-rata pasar saham melakukan rebound (naik kembali), begitu the Fed menurunkan fedfund..
Namun di sisi lain, terdapat hal yang sangat menakutkan dari aksi "kepahlawanan" Kerviel ini, karena ternyata seorang pialang yunior dari mejanya di lantai 6 sebuah gedung sebelah barat Paris, dengan mudah - meski tidak sengaja -, telah menyetir seluruh perekonomian dunia!
Seorang anak muda berpendapatan 100 ribu euro setahun, yakin bahwa dirinya telah menemukan formula transaksi yang baru. Dia dapat melakukan transaksi yang di luar kewenangannya di pasar dengan nilai hampir 50 miliar euro, atau sekitar Rp 690 triliun, atau setara dengan PDB Kuba atau Slovenia, atau kalau dibelikan mobil seharga Rp 1 miliar bisa dapat 690 ribu mobil!!!
Selama tahun 2007 lalu, Kerviel telah melakukan transaksi tersembunyi secara besar-besaran saat sesi larut malam, terpisah dari pekerjaan sehari-harinya dan dia mendapatkan keuntungan besar yang ironisnya membuat dia sulit menjelaskan kepada bosnya darimana keuntungan yang besar tersebut.
Alih-alih dia mengambil uangnya dan melarikan diri, Kerviel malahan merencanakan agar "kalah" dalam perdagangan bulan ini. Namun celakanya, Kerviel kebablasan kalah, akibat pasar saham yang mulai melemah sejak 10 hari lalu, sehingga melayanglah uang 1,4 miliar euro milik SocGen.
SocGen akhirnya menyadari apa yang terjadi akhir pekan lalu. Bank terbesar kedua di Perancis sepertinya berusaha untuk lepas tangan atau tidak mengakui transaksi-transaksi yang dibuat Kerviel, yang justru membuat pasar Eropa pada Senin (22/1) dan Selasa (23/1) jungkir balik. Sehingga bankir saingannya, menyebut bahwa Kerviel "hanya" kehilangan 1,4 miliar euro, sedang sisanya diakibatkan oleh Dewan Direksi SocGen.