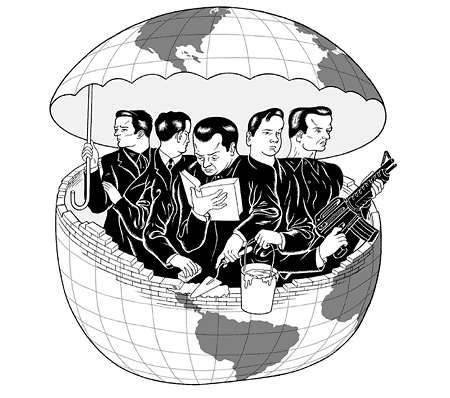Kompas, Jumat, 8 Agustus 2008 | 03:00 WIB
Banyak pengamat internasional berpandangan, krisis pangan global dewasa ini adalah malapetaka buatan manusia. Krisis terjadi karena sektor pertanian di negara-negara berkembang dihancurkan lewat rezim perdagangan global demi kepentingan segelintir pemain besar dari negara maju. Tujuannya, untuk menciptakan ketergantungan pada impor pangan dari negara maju.
Bank Dunia dalam laporan World Development Report berjudul Agriculture for Development mengungkapkan, sektor pertanian dan pedesaan menderita karena selama 20 tahun terakhir terabaikan dan nyaris tak ada dana mengalir untuk inovasi budidaya dan teknologi (underinvestment).
Alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pertanian (termasuk untuk subsidi serta riset dan pengembangan) terus menyusut. Akibatnya, produksi terus stagnan.
Di negara-negara sub-Sahara Afrika, yang pertumbuhan ekonominya nyaris sepenuhnya mengandalkan pada sektor pertanian, rata-rata alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pertanian hanya 4 persen dari total anggaran belanja pemerintah. Itu pun, sektor pertanian masih dipajaki tinggi.
Pada saat bersamaan, alokasi bantuan luar negeri untuk pertanian juga terus menyusut, hanya 4 persen dari total Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) pada tahun 2004. Padahal, 75 persen penduduk miskin negara berkembang hidup dari sektor ini.
Karena itu, menggenjot investasi secara besar-besaran di sektor pertanian menjadi kata kunci untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di negara-negara miskin, sekaligus untuk mencapai target pengurangan angka kelaparan dan kemiskinan hingga separuhnya pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam target Sasaran Pembangunan Milenium (MDG).
Di tengah absennya kepemimpinan global dalam mengatasi krisis pangan sekarang ini, solusi kembali ke pertanian mungkin adalah solusi yang paling riil untuk dilakukan. Ironisnya, ini disampaikan oleh lembaga yang selama ini dituding ikut menyemai krisis pangan global yang kita hadapi sekarang ini.
Apa yang terjadi di Afrika dan sejumlah negara Asia pada kurun 1970-an hingga 1990-an menjadi bukti bahwa lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang selama ini dituding lebih banyak mewakili kepentingan negara-negara maju, telah menjadi bagian kekuatan globalisasi yang justru menghancurkan sistem ketahanan pangan negara-negara berkembang.
Ketika itu, atas nama Program Penyesuaian Struktural (SAP), IMF dan juga Bank Dunia memaksa negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) memangkas drastis anggaran pemerintah untuk berbagai sektor, khususnya untuk program pertanian, sebagai prasyarat untuk bisa terus mendapatkan kucuran utang dari lembaga tersebut.
Termasuk di sini, dengan menghapuskan atau memangkas berbagai program subsidi bagi petani dan memaksakan pemrioritasan budidaya tanaman komersial yang bisa diekspor agar bisa mendatangkan devisa (yang kemudian dipakai untuk membayar kembali cicilan dan pokok utang pada kreditor, termasuk Bank Dunia).
Haiti adalah contoh nyata. Di negara ini beras sudah merupakan tanaman pangan tradisional sejak berabad-abad lalu. Hingga 20 tahun lalu, petani negara ini masih mampu memproduksi sekitar 170.000 ton beras per tahun, cukup untuk menutup 95 persen konsumsi domestik.
Kendati tak mendapat subsidi dari pemerintah, akses mereka ke pasar domestik terproteksi oleh adanya tarif impor yang menghambat masuknya beras impor.
Kondisi berubah tahun 1995 ketika kesulitan ekonomi memaksa pemerintah masuk dalam perangkap IMF. Untuk mendapatkan kucuran utang dari IMF, IMF mensyaratkan Haiti memangkas tarif impor beras dari 35 persen menjadi 3 persen. Hasilnya bisa diterka, beras dari Amerika Serikat segera membanjiri pasar lokal pada harga separuh dari tingkat harga beras produksi lokal.
Ribuan petani setempat jadi kehilangan lahan dan mata pencarian karena tak bisa bersaing dengan beras AS. Dewasa ini, 75 persen beras yang dikonsumsi Haiti adalah beras impor dari AS. Beras AS mampu menggusur beras lokal bukan karena rasanya lebih enak atau karena petani AS mampu memproduksi beras lebih efisien, melainkan karena petani AS disubsidi habis-habisan oleh pemerintahnya.
Tahun 2003, subsidi yang dikucurkan Pemerintah AS kepada petaninya mencapai 1,7 miliar dollar AS atau rata-rata 232 dollar AS per hektar padi yang ditanam. Subsidi ini masuk ke kantong segelintir tuan tanah yang menguasai lahan sangat luas atau perusahaan agrobisnis, dan memungkinkan mereka menjual beras pada harga 30-50 persen di bawah biaya produksi riil.
Di 30 negara terkaya di dunia, subsidi menyumbang 30 persen pendapatan petani, dengan total nilai subsidi yang disalurkan mencapai 280 miliar dollar AS tahun lalu.
Di balik kebijakan ini, ada tujuan lain negara-negara maju, yakni mengurangi kompetisi dan mencegah gejolak pasar, seperti anjloknya harga dunia yang bisa mengganggu kepentingan pemain-pemain besar untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari pasar (Alex Lantier: The World Food Crisis and The Capitalist Market).
Politik imperialisme itu mengakibatkan banyak negara miskin di Afrika dan Asia tak lagi swasembada pangan dan menjadi rentan terhadap gejolak harga pangan dunia.
Paksakan GMO
Modus lainnya yang dipakai adalah melalui kedok ”bantuan pangan”. Politik bantuan pangan yang diterapkan AS selama ini, misalnya, ternyata lebih dimaksudkan untuk melayani kepentingan raksasa agrobisnis dan juga perusahaan-perusahaan perkapalan AS, yakni dalam rangka memperluas pasar mereka.
Berbeda dengan negara-negara lain, bantuan pangan AS mensyaratkan bantuan yang diberikan diproduksi, diproses, dan dikapalkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan AS. Tentu saja ini sangat mahal, membebani negara penerima dan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan AS sendiri.
Demi kepentingan bisnis segelintir konglomerat bioteknologi, benih hasil rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO) juga dipaksakan ke petani negara-negara berkembang dalam konteks ”program bantuan pangan”.
Dalam kasus di Etiopia, benih GMO disalurkan sebagai bantuan bagi petani miskin yang mengalami kekeringan parah. Setelah ditanam dan panen, baru petani menyadari bahwa benih hasil panenannya ternyata tidak boleh ditanam lagi, tanpa membayar royalti kepada produsen benih.
Bukan itu saja, benih tersebut ternyata juga hanya bisa tumbuh jika memakai pupuk, insektisida, dan herbisida yang juga diproduksi oleh produsen yang sama. Di sini, perekonomian petani dijebak masuk dalam perangkap ketergantungan di tangan konglomerat agrobisnis negara maju, seperti Monsanto, Syngenta, Aventis, DuPont, Dow Chemical, Cargill, dan ADM.
Siklus pertanian tradisional yang memungkinkan petani melakukan reproduksi benih di tingkat petani sendiri—yakni dengan menyisihkan benih organik dari hasil panenannya untuk ditanam pada musim tanam berikutnya— menjadi terputus. Akibatnya, tragedi kelaparan terus berulang.
Gagalnya kapitalisme
Kalangan pengamat mencatat semakin terglobalisasi dan terkonsentarsinya produksi pangan global sejak 1970-an. Dewasa ini, perdagangan komoditas pangan pokok didominasi hanya oleh segelintir pemain besar.
Sekitar 80 persen pasar ekspor gandum dikuasai hanya oleh enam pemain. Hal serupa terjadi pada 85 persen pasar ekspor beras. Untuk jagung, 70 persen pasar ekspor bahkan hanya dikendalikan oleh tiga pemain. Ini membuat nasib negara-negara termiskin yang harus mengimpor pangan untuk bisa bertahan hidup menjadi sepenuhnya ada di tangan segelintir korporasi.
Food & Water Watch mencatat, lahan pertanian tanaman pangan di Afrika sejak WTO efektif terbentuk terus menyusut. Sebaliknya, luasan lahan untuk tanaman komersial, seperti kopi, kakao, tebu, kapas, tembakau, dan teh, terus meningkat pesat.
Presiden Venezuela menggambarkan krisis pangan dewasa ini sebagai bukti nyata kegagalan model kapitalisme global. Mantan Presiden Kuba Fidel Castro Ruiz bahkan menyebut program biofuel yang diprakarsai AS dan Uni Eropa sebagai genosida.
Mantan analis pemerintahan federal AS, Richard Cook, dalam tulisan Crisis in Food Prices Threatens Worldwide Starvation: Is It Genocide sependapat dengan Bank Dunia, kini saatnya kembali ke sawah. Dalam kaitan ini, ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan penuh dari pemerintah, mulai dari kredit lunak, jaminan harga, pelayanan yang terjangkau, kebijakan pajak yang mendukung dan hingga yang ekstrem: gerakan nasional untuk mengonsumsi produksi dalam negeri.
”Produksi pangan tidak boleh lagi diserahkan ke tangan perusahaan agrobisnis dan kapitalisme finansial internasional,” ujarnya. (sri hartati samhadi)
sri hartati samhadi Dapatkan artikel ini di URL:
http://entertainment.kompas.com/read/xml/2008/08/08/01295845/dihancurkan.oleh.rezim.perdagangan.global