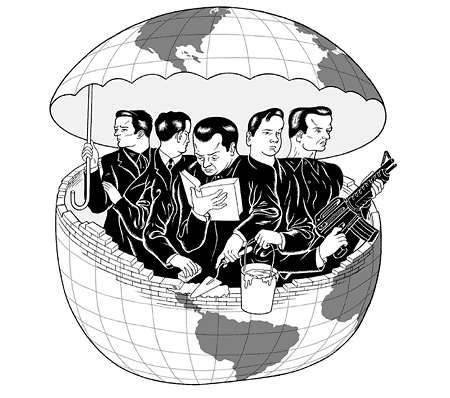Mahasiswa FTW
Bahan bacaan berisi ajakan untuk menolak UU No.13 Th. 2003 tentang ketenagakerjaan dan revisinya di Indonesia. Penolakan itu berdasarkan pemahaman bahwa UU tersebut tidak adil karena lebih memihak para pemilik perusahaan dan sangat merugikan kaum buruh. Lahirnya UU tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam memenuhi permintaan modal asing yang dipaksakan oleh WTO dan IMF demi liberalisasi pasar. Undang-undang No. 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan, bersama UU No.21 th 2000 tentang Serikat Pekerja dan UU No.2 th 2004 tentang PPHI, mengganti UU No.22 th 1957 dan UU No.12 th 1964 sebelumnya yang lebih memberikan perlindungan bagi buruh oleh pemerintah berupa kepastian kerja dan perlindungan sosial. Keberatan utama terhadap UU No. 13 th 2003 tersebut adalah bahwa pemerintah lepas tangan (tidak memberikan perlindungan kepada kaum buruh) dan menyerahkan sepenuhnya masalah perburuhan pada mekanisme pasar. Hal ini ditunjukkan dengan isi UU tersebut yang menghilangkan jaminan hak atas pekerjaan, melegalisasikan praktik-praktik sistem kerja kontrak ilegal dan outsourcing, melepaskan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk melindungi buruh dalam mempertahankan hak atas pekerjaannya, mengekang serikat buruh dan melegitimasi kebijakan upah murah.
Pasal-pasal yang direvisi dalam UU No.13 th 2003 dan berdampak buruk bagi buruh, antara lain pasal mengenai buruh kontrak dan outsourcing, upah, cuti, jaminan sosial, PHK dan uang pesangon, kesalahan berat dan skorsing, kebebasan berserikat, mogok kerja, dan tenaga kerja asing. Penjelasan bahwa pasal-pasal tersebut merugikan kaum buruh adalah demikian. Penerapan sistem kontrak dan outsourcing secara jelas memperlemah posisi buruh karena tidak ada kepastian kerja, kepastian upah, jaminan sosial, THR dan tunjangan kesejahteraan lainnya. Legalisasi sistem ini, dengan waktu masa kontrak dijadikan 5 tahun, akan mengakibatkan PHK amat banyak dan pengalihan status buruh tetap menjadi (seluruhnya) buruh kontrak atau outsourcing. Upah pensiun dengan demikian tidak ada dan jaminan sosial bagi buruh menjadi hilang. Buruh tidak memiliki posisi tawar kuat dan terjerat dalam persaingan pencarian kerja yang ketat. Dampaknya, buruh terpaksa menerima upah berapapun daripada perusahaan mencari pekerja lainnya yang tersedia banyak. Penetapan upah minimum (UMK/UMP) berdasarkan kemampuan sektor usaha yang paling lemah/marginal dan hanya sebagai jaring pengaman saja, akan cenderung dijadikan dasar bagi perusahaan menengah dan besar untuk serendah mungkin membayar upah buruhnya meski sebenarnya perusahaan memiliki kemampuan yang lebih dari itu. Penghilangan pasal hak cuti secara jelas mengurangi kesejahteraan buruh. Peraturan PHK yang lebih mudah, uang pesangon maksimal 7 bulan upah, dan uang penghargaan bagi masa kerja diatas 5 tahun dengan besar maksimal 6 bulan upah, jauh lebih merugikan buruh dibanding peraturan-peraturan sebelumnya. Perusahaan terbebas dari kewajiban membayar pesangon dan memberi hak buruh lainnya bila perusahaan menutup produksi karena alasan forced majeur. Perusahaan juga akan diperbolehkan untuk melakukan skorsing kepada buruh yang melakukan kesalahan berat. Kebebasan berserikat yang tampaknya dipermudah sebenarnya justru membatasi karena tidak ada jaminan perlindungan bagi buruh yang mengikuti kegiatan serikat buruh. Sistem kontrak dan outsourcing akan membuat buruh untuk takut berserikat karena lebih mengutamakan jaminan atas kelanjutan masa kontraknya. Hak mogok kerja yang terbatas hanya bila perundingan gagal dan di tempat kerja saja akan mengekang kekuatan buruh. Keterbukaan pemerintah dengan mempermudah kehadiran tenaga kerja asing akan mengalahkan buruh dari dalam negeri karena pada umumnya tenaga kerja asing memiliki ketrampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Padahal, jumlah rakyat Indonesia yang menganggur telah mencapai angka 42 juta orang.
Fenomena UU No.13 th 2003 tentang ketenagakerjaan ini menjadi bukti dari dampak buruk globalisasi ekonomi zaman ini yang sering disebut dengan race to the bottom. Persaingan diantara negara-negara berkembang memaksa pemerintah Indonesia untuk membatalkan berbagai peraturan yang bersifat protektif demi memperebutkan investasi asing. Pemerintah Indonesia secara jelas ingin mengupayakan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pasar bebas tanpa mempedulikan peningkatan eksploitasi terhadap buruh yang menjadi efek negatifnya. Pertanyaan mengenai siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan atas kebijakan ini selalu pantas untuk dipikirkan. Hakikat bahwa hukum (aturan perburuhan) semestinya hadir untuk melindungi kepentingan buruh ternyata diingkari. Perekonomian negara dijadikan dalih untuk mengedepankan kepentingan pemilik modal dengan menjadikan kaum buruh sebagai tumbal. Pemerintah yang seharusnya hadir untuk melindungi justru takluk dan menjadi alat bagi kepentingan kapital. Dengan demikian, labour market flexibility sebenarnya hanyalah agenda para pendukung neoliberal untuk mengikis proteksi (job security) negara atas kaum buruh. Segala hal telah tereduksi menjadi hanya sebatas persoalan untung-rugi dengan menelantarkan persoalan kemanusiaan yang semestinya menjadi pertimbangan utama untuk itu.